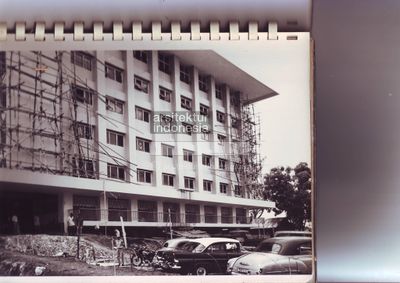Demi Kesederhanaan dan Kejelasan: Arsitektur F. Silaban
Oleh: Setiadi Sopandi | Selasa, 4 Juli 2017
Bagi saya arsitektur yang baik adalah arsitektur yang sesederhana mungkin, seringkat mungkin dan sejelas mungkin. Semua hal-hal yang tidak mutlak dibutuhkan oleh suatu gedung untuk bergunsi sebaik-baiknya sebaiknya jangan diadakan, demi kesederhanaan dan kejelasan.
Kutipan di atas diambil dari makalah yang ditulis oleh Friedrich Silaban, yang disajikan pada Kongres Nasional II Ikatan Arsitek Indonesia di Yogyakarta tanggal 3 Desember 1982. Tajuk artikel ini, “Idealisme Arsitektur dan Kenyataannya di Indonesia”, seakan akan membicarakan hal-hal yang abstrak dan teoritik. Namun sepanjang uraian di makalah tersebut, Silaban membicarakan ‘hanya’ hal-hal yang sering kita juluki ‘teknis’ dan ‘normatif’. Beberapa kata kunci yang dinyatakan Silaban di sana, diantaranya yang terpenting adalah “iklim”, “angin”, “hujan”, “panas matahari”, “emper”, dan “atap”. Seluruh uraian merujuk pada keseharian dan bagaimana bangunan dapat melayani keseharian penggunanya, dengan berusaha menanggulangi ‘masalah’ seperti panasnya sinar matahari dan hujan deras tropis. Kedua hal tersebut, oleh Silaban, didefinisikan sebagai masalah yang harus ditanggulangi.
Dan masalah tersebut senantiasa hadir di setiap penugasan yang ditangani olehnya dan oleh setiap arsitek yang berpraktek di Indonesia. Pernyataan masalah ini begitu lugas dan mudah dimengerti, sebagaimana jawabannya: atap haruslah menaungi seluruh bagian bangunan termasuk dinding-dinding luar bangunan dari hujan deras dan panas matahari. Sedikit lebih jauh, volume ruang-ruang dalam bangunan haruslah dipertimbangkan terhadap banyaknya manusia yang akan menggunakannya, lagi-lagi karena menghindari panas dan sesak yang dapat ditimbulkan.
Meskipun demikian teknis, makalah ini sebenarnya berlandaskan beberapa pijakan subyektif. Diantaranya adalah keengganan Silaban untuk merujuk pada bentuk-bentuk arsitektur tradisional, karena “peniruan” adalah sebuah upaya yang “dicari-cari” bahkan “dipaksakan”, sementara ‘arsitektur Indonesia’ itu menurut hematnya haruslah “modern” dan “tropis”.
Dalam ingatan dan wawasan saya yang pendek, tidak banyak sosok kreatif yang sekonsisten dalam pernyataan dan karya seperti Friedrich Silaban. Silaban tidak banyak menteorikan arsitekturnya lebih jauh dari menjelaskan prinsip-prinsip yang dipegangnya teguh. Karya-karyanya juga tergolong sederhana dan lugas, sehingga tidak terlalu sulit dibaca. Kita dapat memahami kenapa dan bagaimana massa-massa gedung yang lugas dan rapi – tidak sembarang bertemu -, teritisan yang jauh menjangkau, sirip-sirip beton penahan matahari, emper-emper yang luas membungkus massa bangunan.
Namun ada masalah. Bila kita berusaha memahami seluruh karya Silaban secara utilitarian sebagaimana yang tertulis, kita sulit melihat bahwa di balik deretan karya-karya yang utilitarian ini sebenarnya sebuah bahasa simbolik baru – sebuah atribut identitas nasional – tengah dikembangkan pada saat itu. Diktum kesederhanaan dan kejelasan – dua kredo utama dari Gerakan Arsitektur Modern – pernah diadopsi oleh penugasan-penugasan arsitektur oleh negara kita dan dijadikan sebuah bahasa baku yang dianggap dapat menjembatani keragaman dan keluasan suku bangsa, budaya, serta agama. Lebih jauh bahasa tersebut juga dapat menjembatani kita kepada masa depan yang egaliter dan setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia.